22
November 2014
SUBUH
masih pekat, kedua bola mata saya menjelma purnama, bulat, mengusir kantuk
yang sebenarnya jauh sebelum subuh datang pun dia hanya mengintip malu-malu. Semalaman
saya tidak bisa tidur. Memang, sejak beberapa tahun yang lalu saya menderita
insomnia akut, dan meski kini sudah bekerja, “musuh tengah malam” itu masih
enggan beranjak dari tubuh saya yang kata orang kian cungkring.
Hah!
Memang kebiasaan saya sejak dulu, setiap kali akan ada momen penting dalam
hidup, satu malam sebelum hari itu datang saya pasti berubah resah, gelisah, dan
tak bisa tidur. Padahal saya masih jomblo, lho. Oke, lupakan itu.
Bait
terakhir kumandang adzan baru saja usai, saya menyiapkan kemeja putih dan
celana bahan yang akan saya pakai hari ini. Ini adalah hari istimewa untuk saya
dan keluarga, terlalu istimewa. Betapa tidak, hari ini adalah hari di mana
keluarga besar kami akan mencatat sejarah baru dalam rentang hidup yang panjang
keturunan Mak Wak (nenek). Saya akan menjadi sarjana pertama dari keluarga
persukuan nenek, karena kami di Minang menganut sistem kekerabatan matrilineal.
Saya
telah selesai mandi. Ruang tengah rumah Ante Yen (tempat saya tinggal dan
menjadi tempat berkumpulnya keluarga besar di Serang) pun mulai sibuk. Empat
pasang mata memperhatikan saya memakai pakaian wisuda dan toga. Ada binar di
mata Amak, Abak, Ante Us, juga Mak Wak. Ah, saya merasa berdosa demikian terlambat
mempersembahkan ini pada mereka. Enam tahun menghabiskan waktu untuk kuliah bukanlah
masa yang sebentar. Tapi tidak apa-apa, saya pun tahu mereka pasti bisa
memahami.
Saya
tidak pernah mengira, pamandangan pagi ini akan kembali dapat saya saksikan,
melihat kedua sosok manusia paling berjasa dalam hidup saya—Amak dan Abak. Tidak
ada yang perlu saya tutup-tutupi, kedua orangtua saya berpisah 2005 silam. Kala
itu saya baru lulus SMP. Barangkali atas dasar sakitnya perpisahan itu yang
membuat saya betah di rantau. Terlebih keadaan ekonomi Abak yang tak mungkin
saya andalkan untuk menumpangkan cita-cita, juga Amak yang hidup dengan
penghasilan warung yang pas-pasan, saya memutuskan untuk meninggalkan kampung
halaman.
Masa
SMA saya lalui di kaki Lembah Harau dan pinggir Danau Maninjau, Sumatra Barat. Di Tanjung Pati saya tinggal
bersama Tak Rus dan membantu usaha fotokopinya sepulang sekolah dan di
Maninjau saya mendapat beasiswa selama 2,5 tahun. Gerbang remaja terbuka lebar saat itu. Segala rasa dan
pengalaman bebas keluar masuk, namun di masa “pemulihan jiwa” pascaperpisahan
Abak dan Amak itu, duka mengambil tempat lebih banyak. Tak jarang saya meratapi
nasib, memandang langit tengah malam, dan tersedu mengadu pada Tuhan. Entahlah,
saya sendiri telah lupa bagaimana cara saya bertahan di masa itu. Yang pasti—hari
ini saya masih hidup dan akan diwisuda dalam beberapa jam ke depan dalam
keadaan bahagia.
Tol
masih sepi. Hanya beberapa kendaraan yang melaju. Matahari pagi menemani
perjalanan saya dan keluarga ke The Royale Krakatau Hotel, tempat
diselenggarakannya acara wisuda gelombang III tahun 2014 oleh kampus saya,
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Langkah saya terasa gagah. Hati pun demikian
lapangnya. Ya, kesakitan masa lalu itu telah hilang. Saya yang mengusirnya. Itu
juga yang membuat kadar kekecewaan saya yang lama tercatat sebagai mahasiswa
menjadi berkurang. Enam tahun di Banten, demikian banyak pengamanan yang saya
cicipi. Demikian banyak jiwa-jiwa yang tenyata lebih sakit dari kesakitan saya,
yang pada akhirnya menyadarkan saya bahwa tiada guna menyimpan sakit. Sakit
yang dipelihara dalam jiwa seperti menanam benalu di pohon mangga. Sia-sia.
Senyum
bangga kedua orangtua saya jauh lebih berharga. Dan saya lebih memilih itu.
***
Sepuluh.
Dua puluh. Lima puluh. Ah, saya tak mampu lagi mengitung. Banyak tangan
melambai di depan saya. Banyak mata yang memerah dan sembab. Banyak sedu
haru-biru. Ada bapak yang memeluk putrinya. Ada ibu mencium putranya. Saya
mencari-cari Amak dan Abak, saya ingin diperlakukan serupa.
Aroma
lumpur di badan Abak masih seperti dulu. Aroma baju tua Amak juga tak berubah.
Meski dari subuh Amak telah dibaluti kebaya merah dan Abak berbatik warna
senada—yang baru lepas segel, aroma mereka tetap seperti dulu. Yang berbeda
hanya kerutan di wajah yang kini kian jelas, terlebih Abak, beberapa giginya
telah tanggal. Abak terlihat lebih tua dari usianya. Sudahlah, tak ada yang
perlu disesali, demikian kata Abak pada saya dalam beberapa kali percakapan
kami di telepon.
Tab
saya berdentang. Ucapan selamat dari kawan-kawan di BBM, SMS, WhatsApp, dan Facebook
membanjiri. Di depan saya beberapa tangan melambai-lambai. Hilal, Ali,
Naminist, Bembi, Asep, Ayah Rusli, Dhiva… ah, tiba-tiba saya merasa demikian
kaya.
“Selamat
ya… akhirnya wisudaaa!!!”
“Bangga
dong, Sarjana Teknik. Maju ke level selanjutnya, ya!”
Banyak
doa yang datang. Doa-doa yang saya kumpulkan untuk bahan bakar agar kapal
impian terus melaju. Karena perjalanan menuju pulau impian yang sesungguhnya
baru saja dimulai. Kapal tempat impian keluarga besar pun ditumpangkan. Kapal
yang membawa bibit "baringin di tangah padang". (Baringin di tangah
padang adalah kutipan pepatah adat Minangkabau yang menggambarkan sosok
seorang laki-laki dalam menjalani kehidupan).
Baringin di tangah padang – Beringin di tengah padang
Dedi Setiawan, S.T.
Baringin di tangah padang – Beringin di tengah padang
Baurek
cakam ka tanah – Berakar menghujam
tanah
Jauah tahunjam ka pitalo – Jauh terhujam ke dasar bumi
Panuahlah bumi dek rumpunnyo – Penuhlah bumi karena rumpunnya
Dek gampo indak tabongkehkan – Tak akan tumbang oleh gempa
Karano badai alun taoleang – Tak akan goyah oleh badai
Kununlah guyang angin lalu – Hanya bergerak karena angin berembus
Taguah pandirian – Teguh pendirian
Batauhid sarato istiqomah – Bertauhid dan istiqomah
Kukuah sarato yakin – Kokoh dan teguh pendirian
Kok yakin tumbuah dipaham – Ketika yakin pada sesuatu yang benar
Sajangka duduak indak bakisa – Sejengkal duduk pun tidak akan bergeser
Satampok tagak indak bapaliang – Tegak tidak akan berpaling
Walau baalah bujuak rayu – Walau bagaimanapun bujuk serta rayuan
Haram kuniang karano kunyik – Tidak akan kuning dilumuri kunyit
Pantang lamak ulah dek santan – Pantang enak biar pun disantani
Rugi jo pitih indak ditimbang – Rugi dan uang tidak menjadi pertimbangan
Jariah jo payah soal biaso – Susah dan payah bukanlah masalah
Jauah tahunjam ka pitalo – Jauh terhujam ke dasar bumi
Panuahlah bumi dek rumpunnyo – Penuhlah bumi karena rumpunnya
Dek gampo indak tabongkehkan – Tak akan tumbang oleh gempa
Karano badai alun taoleang – Tak akan goyah oleh badai
Kununlah guyang angin lalu – Hanya bergerak karena angin berembus
Taguah pandirian – Teguh pendirian
Batauhid sarato istiqomah – Bertauhid dan istiqomah
Kukuah sarato yakin – Kokoh dan teguh pendirian
Kok yakin tumbuah dipaham – Ketika yakin pada sesuatu yang benar
Sajangka duduak indak bakisa – Sejengkal duduk pun tidak akan bergeser
Satampok tagak indak bapaliang – Tegak tidak akan berpaling
Walau baalah bujuak rayu – Walau bagaimanapun bujuk serta rayuan
Haram kuniang karano kunyik – Tidak akan kuning dilumuri kunyit
Pantang lamak ulah dek santan – Pantang enak biar pun disantani
Rugi jo pitih indak ditimbang – Rugi dan uang tidak menjadi pertimbangan
Jariah jo payah soal biaso – Susah dan payah bukanlah masalah
Dedi Setiawan, S.T.
Saya yang masih terus belajar menjadi baringin di tangah padang
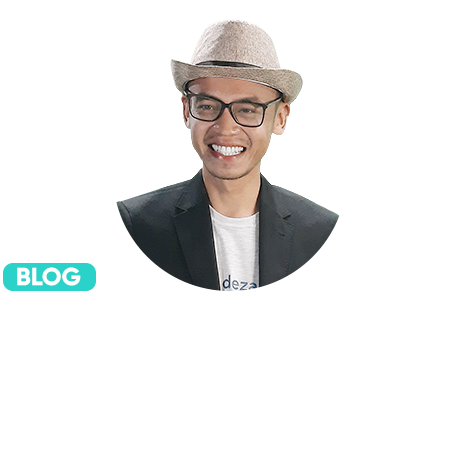

























1 Komentar
selamat uda....:)
BalasHapusSILAKAN TINGGALKAN KOMENTAR (◠‿◠)