Siapa yang bisa memberikan jaminan pasti bahwa Anda –sebagai penulis yang telah menerbitkan beberapa bahkan puluhan (ratusan?) buku– menyangka bahwa menulis buku itu sangat mudah. Bahkan dari sangkaan itulah lama-kelamaan berubah menjadi sedikit kesombongan bahwa menulis itu urusan kecil, ah sepele, yang beginian gua juga bisa, cuma bisa begitu aja nulis… atau nggak akan ada yang bisa nulis buku seperti apa yang gue tulis.
Terkadang urusannya bisa merembet soal berapa rupiah yang akan didapatnya. Jika ada penerbit yang meminta naskah kepadanya sebuah pertanyaan standar akan dilontarkan, “Kalau satu halaman 150 ribu rupiah, mau? Royalti 15 persen, deh!”
Akhirnya, mungkin sebagian kita bisa menebak, jika penerbit itu adalah penerbit besar yang punya modal cukup banyak, maka berapapun yang diminta oleh si penulis terkenal itu akan disanggupi. Celakalah bagi penerbit yang modal pas-pasan atau mereka yang baru kecebur di bidang usaha ini dengan kekuatan kapital yang rata-rata; hilanglah harapan untuk menerbitkan buku sang penulis terkenal, hilang juga impian usahanya akan maju dan sukses setelah buku sang penulis terkenal itu sukses di pasaran.
Akhirnya, penerbitpun mencari pengganti; sang penulis pemula atau penulis gagal. Katagori terakhir ini diartikan sebagai (calon) penulis yang naskahnya selalu ditolak penerbit. Juga, dengan bayaran/royakti yang sesuai kemampuan penerbit.
Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya?
Keinginan untuk besar dan memenangkan sebuah kompetisi (pasar) seperti keinginan klub Washington Sentinels untuk memenangkan trofi pertandingan football, sepakbola ala Amerika. Tapi apa yang didapatkan oleh Sentinel? Ternyata bayaran yang besar tidak membuat keinginan itu tercapai. Sebaliknya para pemain mogok untuk bertanding dan celakanya mereka malah menuntut kenaikan gaji yang kadung sudah besar itu; perhatikan bagaimana sang bintang lapangan Eddie Martel sengaja untuk tidak bermain cemerlang hanya dengan alasan takut cedera, padahal semestinya ia tahu bahwa football adalah olahraga yang kerap melakukan kontak fisik .
Pusing tujuh keliling memikirkan bagaimana caranya untuk memenangkan turnamen, sang pemilik Edward O’Neil akhirnya menyewa seorang pelatih Jimmy McGinty. Targetnya hanya satu, mencari pemain pengganti dan memenangkan pertandingan yang tersisa. “Kita hanya perlu tiga kemenangan saja untuk masuk babak playoff,” kata sang pemilik. “Ya, tapi saya akan melatih sesuai dengan gaya dan keinginan saya,”demikian tawa McGinty. Kata sepakat pun tercapai.
Akhirnya, Sentinel bertanding dengan para pemain pengganti. Shane Falco didapuk menjadi kapten bagi rekan-rekannya. Siapa Falco? Dulu dia adalah pemain handal dan seorang quarterback terkenal dari Ohio State University. Akan tetapi karena satu kesalahan, membuat Falco harus mengubur impiannya menjadi pemain football nasional dan menjadi petugas pembersih kapal di dermaga.
Falco bukanlah satu-satunya orang yang gagal. Nigel Gruff pemain pengganti bernomor punggung #3 adalah pemilik klub yang tidak bisa menendang bola; Clifford Franklin bernomor punggung #81 merupakan staf gudang sebuah mini mart yang pandai berlari, tetapi tidak bisa menangkap; Earl Wilkinson alias “Ray Smith” seorang narapidana karena kasus pemukulan terhadap petugas polisi. Dan kegagalan tim ini dilengkapi oleh sang pelatih sendiri yang dulunya pelatih Sentinel namun dipecat gara-gara berbeda pendapat dengan bintang tim.
Lengkaplah penderitaan tim ini. Ditambah dengan pertemuan pertama mereka yang dibabat habis oleh tim lawan. Namun, seiring waktu, mereka pun memenangkan pertandingan demi pertandingan. Bahkan tinggal satu kesempatan lagi akan membawa Sentinel ke babak playoff.
Di sinilah klimaks itu terjadi. Ketika tinggal satu pertandingan penentuan lagi, sang mega bintang tim yang mogok Martel ‘kembali’ dan ingin bermain—tentu saja mau menjadi bintang pujaan ketika tim ini menang. Sang pelatih tidak bisa berbuat apa-apa karena intervensi pemilik klub. Lalu Falco, yang posisinya direbut, hanya mengatakan, “Kalau kembalinya Martel untuk kebaikan tim, dia lebih baik dari saya.”
Falco mengalah. Martel bermain dan menjadi quarterback. Tapi skor berbicara lain, Sentinel dipermalukan 17-0 diparuh pertama.
McGinty sungguh kesal. Tim yang sudah solid dan dibina dengan Falco sebagai perekatnya berantakan di lapangan. Ia jadi teringat kata-katanya ketika membujuk Falco, “Engkau punya hati dalam bermain, sementara dia tidak.” Kata-kata inilah, dalam versi berbeda, diutarakan McGinty ketika diwawancarai oleh reporter di lapangan, “miles and miles of heart. “ Bahwa kita perlu hati yang bisa ‘menikmati’ permainan ini, bukan sekadar bertanding.
Pesan itu di dengar Falco yang jauh dari stadion. Pesan yang masuk ke hatinya dan membuatnya bergerak menuju stadion dan memenangkan pertandingan itu dengan skor 24-17. Sentinel pun masuk babak playoff.
Di akhir pertandingan, sang pelatih hanya bisa berkata, “Bahwa tidak akan ada perjanjian atau parade kemenangan buat kalian karena kalian bukanlah tim inti klub ini, hanya pemain pengannti untuk empat pertandingan saja. Yang ada hanyalah sebuah loker yang harus dibersihkan dari peralatan dan pakaian kalian untuk diisi kepunyaan pemain inti yang akan bertanding di tingkat nasional setelah kemenangan ini.”
Falco dan rekan-rekannya sudah menyadari nasib seorang pemain pengganti. Ibarat kata pepatah, habis manis sepah dibuang.
“Tapi…,” McGinty melanjutkan, “Bahwa kalian semua mendapatkan kesempatan dan ada di antara kalian yang mendapatkan kesempatan kedua sehingga pada akhirnya kalian bisa keluar sebagai pemenang. Perasaan yang akan abadi sampai akhir nanti.”
Ya, cuplikan film The Replacements yang diperankan Keanu Reeves (Falco) dan Gene Hackman (McGinty) yang dirilis tahun 2000 itu seperti memberi kisah tersendiri. Bahwa persoalan bermain dengan hati adalah persoalan yang bisa menempatkan seseorang, dan tim, mampu menikmati pertandingan yang mereka lakoni. Jika pertandingan diukur dari berapa uang yang selayaknya didapat, maka pertandingan akan dijalani sekadar pertandingan dan tanpa cinta.
Anda, dan saya pun tentunya, sepertinya juga harus menjadi Falco dalam menjalani profesi sebagai seorang penulis. Uang adalah diperlukan dalam hidup ini, namun uang bukan satu-satunya ukuran yang dijadikan standar dalam menghasilkan sebuah karya. Ibarat air garam, batas berapa layak kita dibayar untuk sebuah naskah yang dihasilkan selalu tidak pernah mencukupi. Mungkin tahun ini kita menetapkan standar Rp20 ribu per halaman, bisa jadi tahun depan menjadi Rp100 ribu per halaman. Tahun depan batas itu naik lagi. Dan itu tidak akan pernah sampai titik akhir…
Apabila sebuah karya dinilai dari berapa uang yang didapat, maka terkikis juga lama-kelamaan hati nurani kita sebagai seorang penulis. Kita pun menolak beberapa tawaran penerbit hanya gara-gara pembayarannya yang dianggap tidak sesuai dengan standar kita.
Padahal kita mungkin tidak sadar bahwa mereka, penerbit, sangat berharap kita mau menulis untuk mereka. Menjual buku kita yang laris manis di pasaran dan uang penjualan itu bisa menghidupkan napas kapital penerbit, membiayai keperluan operasional, menggaji karyawan, dan karyawan bisa membeli nasi untuk anak dan istri di rumah. Tidak hanya itu, setiap buku yang laku juga akan bernilai ‘pahala’ karena dibaca dan bermanfaat oleh sang pembaca, baik didapat dari beli atau minjem.
Ya, menulis itu urusan hati. Siapapun bisa cerdas dan pintar, tapi tidak semua penulis bisa memiliki hati yang iklas dan benar. Yang selalu ingat bagaimana dulu dia selalu berdoa kepada-Nya agar naskah yang dibuat mau diterima penerbit, dicetak, dan dipasarkan di toko buku… dengan bayaran berapapun dan sistem pembayaran bagaimanapun. Yang selalu sadar bahwa ketika saat ini dia telah menjadi penulis besa, maka itu adalah kerja tim; kerja tim editor yang mengemas naskah menajdi buku yang luar biasa, bagian marketing yang mengolah buku menjadi barang dagangan laku di pasar, para jurnalis yang mengupas serta meresensi buku sehingga bisa dikenal oleh khalayak, dan sampai pekerja gudang yang dengan sangat hati-hatinya meletakkan, menyusun, dan mendistribusikan ribuan buku yang dia tulis.
Inilah sang pengganti atau replacements yang tidak pernah terpikirkan dalam kehidupan sang penulis.
Inilah sang pengganti atau replacements yang tidak pernah terpikirkan dalam kehidupan sang penulis.
Rasanya mustahil seorang penulis, sekaliber siapapun, mampu mengedit sendiri, melayout halaman sendiri, mendesain kaver sendiri, mencetak dengan mesin cetak sendiri, memotong semua kertas sendiri, menuangkan tinta ke mesin cetak sendiri, membukus buku sendiri, mendistribusikan buku ke toko-toko buku sendiri, me…. Nyendiri…
Merasa bahwa kita punya tangan seperti Raja Midas yang bisa mengubah beberapa lembar kertas HVS ukuran A4 menjadi emas naskah yang tinggi nilai harganya. Menyangka bahwa tidak akan ada calon penulis atau penulis pemula yang juga suatu saat bisa menyamai bahkan melampaui pencapaian yang telah diraih.
Terakhir, berbagilah! Jika kita adalah penulis hebat, maka berbagilah ilmu itu kepada orang lain. Karena ibarat kata-kata bijak, “beramal dengan harta akan hilang bekasnya dalam sekejap, namun beramal dengan ilmu seperti mengukir di atas batu yang akan abadi”. Ah, saya jadi lupa apakah ini kata-kata bijak dari seorang filosof atau salah satu syair dari lagu kasidahan yang dulu pernah saya dengar.
Maka, menulislah dari hati!
Jika tidak, betul kata Bang Rhomah.. “Huh, terlaluh…!”
Sumber www.menulisyuk.com
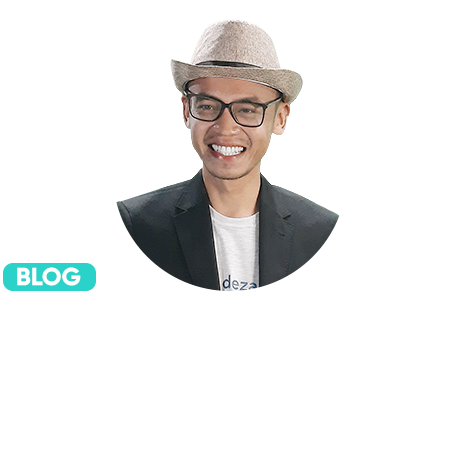







0 Komentar
SILAKAN TINGGALKAN KOMENTAR (◠‿◠)